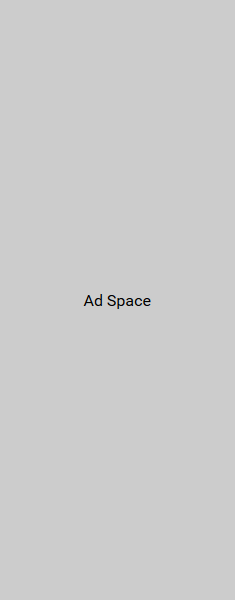Caping Gunung Indonesia - Catatan tindak kriminalitas seksual terhadap anak di Indonesia bertambah panjang. Seorang ibu berinisial MF melaporkan kejadian pencabulan QZ, anaknya, yang masih duduk di bangku TK Mexindo, Bogor. Pencabulan ini diduga dilakukan oleh seorang penjaga sekolah berinisial U.
Dilansir Kompas, pada Mei silam, MF mendapati anaknya merasa kesakitan saat buat air kecil. Awalnya, MF tidak merasa curiga, tetapi ketika memeriksa celana dalam QZ, ditemukan noda darah. MF pun membawa QZ ke dokter untuk visum. Dari penjelasan dokter, diketahui bahwa ada benda yang dipaksakan masuk ke alat kelamin QZ. Sejak itulah MF menduga anaknya telah menjadi korban pencabulan.
Trauma pun mengiringi QZ sehingga ia sulit diajak berkomunikasi. Setelah dibujuk orangtuanya, QZ pun mengaku dirinya dicabuli oleh penjaga sekolah. Upaya advokasi pun dilakukan MF. Kasus tersebut dilaporkannya ke Pemkot dan Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Alih-alih mendapat dukungan untuk memperoleh keadilan, Pemkot malah lepas tangan dengan mengatakan kasus tersebut berada di luar wewenangnya. MF juga kembali menelan kekecewaan setelah Disdik yang sempat menjanjikan akan menonaktifkan sementara terlapor belum kunjung mewujudkan janjinya.
MF juga melaporkan kasus anaknya tersebut ke Polresta Bogor tanggal 12 Mei lalu. Namun hingga Agustus, penjaga sekolah tersebut belum juga ditangkap atau diberhentikan dari tempat kerja. Alat bukti sudah diserahkan MF, tetapi polisi belum juga bergerak menegakkan keadilan bagi MF dan anaknya.
Menurut pengakuan MF, pihak sekolah bahkan meminta tersangka tidak ditahan dulu. MF kian sakit hati begitu mendapat tanggapan pihak kepolisian yang saat itu memintanya pasrah saja dan mengatakan sudah banyak kasus serupa terjadi.
Kepelikan di Berbagai Sisi
Kekerasan seksual yang dilakukan orang dikenal bukanlah hal langka dalam
catatan kriminal di Indonesia. Berdasarkan laporan fakta kekerasan
seksual di Indonesia dari MAPPI FHUI tahun 2016, tercantum beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan di lingkup institusi pendidikan.
Pada 2014, Sitok Srengenge, pengajar dan sastrawan, dilaporkan mencabuli seorang mahasiswi berinisial RW. Setahun kemudian, seorang mahasiswi UNJ melaporkan dirinya disetubuhi dosen. Alih-alih mendapat keadilan, pelaku malah melaporkan balik korban dengan sangkaan melakukan pencemaran nama baik. Tahun lalu, 22 siswa di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, diduga menjadi korban pelecehan seksual guru Bahasa Inggris.
Anak-anak di bawah umur rentan mengalami kekerasan seksual. KPAI mewartakan, sejak 2013 hingga 2014, statistik pelaku dan korban kekerasan seksual anak naik hingga 100 persen. Sekretaris KPAI, Rita Pranawati menyebutkan, selain kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orangtua dalam mengasuh anak, lingkungan pergaulan juga mendorong maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Isu kepercayaan juga mengambil andil dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut psikolog forensik Lia Sutisna Latif, sering kali korban mengalami kejadian traumatis itu tanpa disangka karena pelaku dianggap bukan pihak yang membahayakan. Dalam kasus QZ, Lia memandang penjaga sekolah dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan rasa aman, padahal kenyataannya, justru oknum itulah yang menjadi predator.
“Hampir semua kejadian kejahatan itu bersifat repetitif. Kejahatan dulu bisa terulang seiring bertambahnya jumlah pelaku yang bertipe serupa,” imbuh perempuan yang juga mengampu Forensik Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK).
Kurangnya edukasi seks yang diterima anak, mulai dari hal dasar seperti pengenalan tubuh dan menjaga diri ketika orang lain ingin menyentuhnya, memang kerap kali disebut sebagai faktor yang menyuburkan fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Kendati demikian, ada faktor-faktor lain yang juga membuat anak menjadi korban kriminalitas ini.
“Kalau dari sisi kepribadian pelaku, bisa jadi terdapat pengalaman trauma pada masa lalu yang tidak pernah ditangani. Ada orang-orang yang merupakan korban (kekerasan seksual), berubah menjadi pelaku saat beranjak dewasa,” kata Lia. Diperlukan pemeriksaan psikologis mendalam untuk menjelaskan ada tidaknya gangguan seksual dalam diri pelaku.
Sering kali, orang menyamakan pedofil dengan pelaku kejahatan seksual anak atau child molester. Padahal kenyataannya, yang patut dijatuhkan hukuman adalah mereka yang telah benar-benar mewujudkan fantasi seksualnya terhadap anak alias si child molester. Tidak semua pedofil merupakan child molester. Untuk itu, Lia mengatakan, perlu dicermati apakah kejadian yang menimpa QZ ini melibatkan child molester atau dilakukan pedofil atau penderita gangguan kejiwaan lain.
Dari sisi anak di bawah umur, aktivitas seksual yang mereka lakukan dengan orang dewasa kerap memposisikan mereka sebagai korban kekerasan seksual. Ini dikarenakan anak diasumsikan belum memahami konsep consensual sex.
Keterlibatan anak dalam aktivitas atau pelecehan seksual dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran anak akan batasan-batasan privat yang tidak semestinya dijamah orang luar, atau bisa pula hadirnya intimidasi pelaku terhadapnya sehingga kejahatan seksual terus terjadi. Bukan hal baru ditemukan berita orang yang sedarah dengan korban melakukan pencabulan anak dan baru terungkap setelah pencabulan itu dilakukan beberapa kali.
Masyarakat dan pihak KPAI menyayangkan kelambanan penegakan hukum untuk kasus QZ ini. Jika dikontraskan dengan kasus pelecehan seksual pada tahun-tahun sebelumnya di tempat lain, seperti di Jakarta International School pada 2014, respons aparat atas kasus QZ ini lebih lama.
Lia berpendapat ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan lambannya proses penegakan keadilan bagi QZ. Pertama, pihak kepolisian menganggap bukti-bukti otentik di pengadilan kurang cukup untuk menjebloskan terlapor ke penjara. Walaupun pada kenyataannya, MF merasa telah menyediakan bukti-bukti tersebut.
“Saksi mata dan saksi dengar pun dibutuhkan untuk menjelaskan kejadian di TKP. Kasus kriminalitas seksual merupakan kasus yang sensitif dan bukan sesuatu yang dapat dengan gampang dan cepat direspons,” ucap perempuan yang juga menjadi anggota pengurus Apsifor (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia).
Mengatasi Trauma Korban
Seiring dengan proses advokasi yang dijalankan keluarga, fokus terhadap kondisi korban pun tidak boleh luput diperhatikan. Dukungan emosional untuk korban perlu diberikan secara maksimal. Bila korban belum bisa mengomunikasikan kejadian buruk yang dialaminya, keluarga atau orang dekat lainnya butuh bersabar dan memahami situasi emosi si korban.
Hal lain yang dapat dilakukan adalah menghindarkan korban untuk kembali ke TKP karena dapat memperburuk kondisi traumanya. Alih-alih meminta korban untuk beraktivitas seperti sedia kala, orangtua perlu memberikan rasa aman dulu kepada korban sebelum ia kembali ke sekolah. “Pahami emosi anak karena sewaktu-waktu, emosinya bisa meledak jika teringat akan kejadian buruk yang menimpanya. Katakan kepada anak, ‘Nak, Mama tahu kamu sedih, tapi sekarang ada Mama di sini yang akan menjaga kamu,’,” ujar Lia.
Tidak semua orangtua memiliki kecakapan menangani trauma. Bahkan dalam kasus tertentu, bukan tidak mungkin orang-orang terdekat dengan individu yang trauma mengalami frustrasi dan malah gagal memberi dukungan moral. Karena itu, pakar psikologi dapat dilibatkan untuk membantu pengentasan masalah psikis korban melalui pendampingan atau terapi.#Lilis_cgo